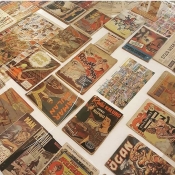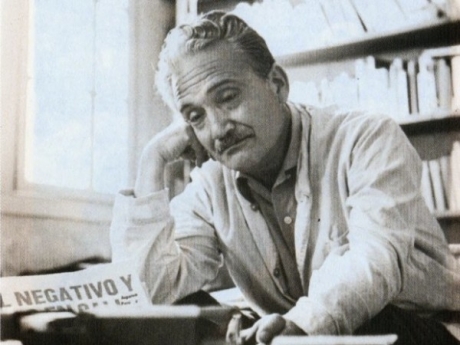
Foto: José María Arguedas, diunduh dari http://stereovilla.pe/el-libro-del-dia-todas-las-sangres-de-jose-maria-arguedas/
Oleh: Feby Indirani
Musim semi adalah saat terbaik untuk mati. Bisa
jadi, dalam hasrat bunuh dirinya, masih terlintas di benak José María Arguedas
untuk merancang hari kematian yang puitis. Ia mungkin sengaja memilih 2
Desember 1969, saat bunga-bunga justru bermekaran di kota tempat tinggalnya di
Lima, Peru.
Di usia 58 tahun, novelis, penyair, dan
antropolog ini menembak dirinya sendiri dalam sebuah ruang kelas kosong di
universitas tempatnya mengajar. Dalam suratnya, salah satu alasan yang
membuatnya memilih mati adalah perasaan bahwa kariernya sebagai penulis telah
tamat. Sebab, ia merasa tak lagi memiliki daya kreatif.
Ia hanya satu dari daftar panjang. Memang, pekerja
kreatif lainnya seperti musisi pun rentan terhadap potensi bunuh diri. Tapi ada
dugaan, dibandingkan seniman lain, penulis lebih mudah tergoda untuk bunuh
diri, sebagai bukti kemampuan mengontrol jalan hidup mereka. Bukankah indah
jika bisa merancang kapan momen terindah untuk meninggalkan dunia ini?
Dari waktu ke waktu, sejarah telah mencatat
begitu banyak penulis yang memilih bunuh diri. Di wikipedia kita bisa
menemukan sekitar 400 nama, jumlah yang masih bertambah dari waktu ke waktu.
Daftar ini mulai dari penulis yang karyanya sudah jadi klasik seperti
Hemingway, Virginia Wolf, Sylvia Plath, sampai Hunter S. Thompson, pelopor
tulisan jurnalistik dengan sudut pandang orang pertama yang masih aktif menulis
sampai era 2000-an.
Karena terkait nilai budaya dan agama, kasus
bunuh diri penulis belum pernah terdengar di Indonesia. Itu kalau kita tak
menyebutkan aktivitas begadang, merokok, dan konsumsi alkohol berlebihan dan
gaya hidup semrawut yang sebetulnya salah satu cara bunuh diri perlahan-lahan,
apakah itu diakui atau tidak oleh pelakunya.
Sekali berarti sudah itu mati, seru Chairil Anwar
(1922-1949) yang merokok mirip bernapas. Dan ia mati sebelum tepat 27 tahun
dengan nama yang terus melegenda hingga hari ini. Berbahagialah mereka yang
mati muda, seru Soe Hok Gie (1942-1969) dalam puisinya yang selalu menggema. Di
usia 27 ia tewas bukan oleh tangannya sendiri, tapi terkena gas beracun di
puncak Semeru. Namun mati muda kian menjadi daya tarik bagi banyak penulis
Indonesia.
Keterkaitan antara penulis kreatif dan hasrat
pada kematian menumbuhkan minat para ilmuwan untuk melakukan studi. Kay
Jamison, profesor psikriatri dari Johns Hopkins University, menyatakan penulis
memiliki kemungkinan 10 hingga 20 kali dibandingkan orang lainnya untuk
menderita manic-depressive, jenis depresi yang paling banyak
mengantarkan ke perilaku bunuh diri ketimbang gangguan mental lainnya. Jadi,
bagi Anda yang ingin jadi penulis, hai-hati! Pekerjaan ternyata bisa
membahayakan kesehatan mental bahkan hidup Anda.
Memang, tidak berarti setiap penulis adalah
pengidap manic-depressive. Begitu pula sebaliknya. Tapi, melalui
penelitian intensif, Jamison menemukan bahwa ciri kognitif penderita depresi
ternyata tumpang tindih dengan watak kreatif. Penderita manic depressive
dalam kondisi normalnya berpikir lebih cepat, mengalir, gampang berubah-ubah,
dan lebih orisinal. Dalam keadaan depresi, subyek ini akan terus mengritik
dirinya, sebuah kerangka pikiran yang membawanya pada kehendak merevisi dan
mengedit.
“Ketika bicara tentang penulis kreatif, kita akan
menemukan keberanian, kepekaan, kegelisahan, dan sikap tak kunjung merasa puas,
inilah temparamen manic-depressive,” kata Jamison, yang mengarang buku Touched
With Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament.
Selain itu, ada pula kesamaan aspek di antara manic-depressive dan kreativitas, yaitu kemampuan tetap berfungsi dengan baik dalam kondisi kurang tidur, konsentrasi bekerja secara intensif, dan kemampuan merasakan beragam emosi secara mendalam. Menarik, ‘kan, melihat betapa banyak kemiripan antara kondisi kreatif dan depresi-mania? Hal serupa tak hanya terjadi pada penulis tapi juga pekerja kreatif lainnya.
***
Ketakuran akan ketakmampuan berkarya diduga menempati ranking cukup penting sebagai penyebab depresi para penulis. Sebagian penulis diduga bunuh diri karena kecemasan bahwa masa keemasannya sudah selesai. Banyak pihak yang menduga Hemingway termasuk dalam jajaran itu. Penyair Anne Sexton justru memuji tindakan bunuh diri Hemingway. “Bagus untuknya!”
Pendapat Sexton juga disetujui Sylvia Plath.
Keduanya berpendapat bahwa kehidupan seorang seniman hebat memang sepatutnya
diakhiri dengan kematian. Berhentilah sebelum kau menulis lebih banyak lagi hal
buruk! Saat Plath mengakhiri hidupnya pada 1963, Sexton pun berkata, “Kematian
adalah bagianku.” Sebelas tahun kemudian, Sexton pun memilih mati bunuh diri.
Di sisi lain, justru ada yang bunuh diri karena
meyakini masa emasnya tak akan pernah tercapai. H.S. Babra adalah salah satu
tragedi. Penulis keturunan India ini bunuh diri di usia 45 tahun. Ia
menerbitkan novel pertamanya, Gesture, pada 1980-an yang tak begitu
meledak. Setelah itu ia sempat melahirkan beberapa novel bergenre misteri dan thriller
yang tak pernah mau ditulisnya dengan nama aslinya. Novel-novelnya ini berhasil
meraih beberapa penghargaan. Tapi, rupanya, bukan karya seperti itu yang
diimpikan Babra. Karena merasa tak akan pernah berhasil melahirkan ‘novel
besar’, ia memilih mengakhiri hidupnya.
Sampai di sini kita bisa melihat, baik ukuran ‘keberhasilan’
maupun ‘kegagalan’ sama-sama bisa mengakibatkan tekanan dan membawa para
penulis membahayakan diri sendiri. Padahal, siapakah yang berhak mengukur
sebuah karya itu besar atau tidak? Redakturkah, kritikus, atau para pembaca?
Berapa banyak yang dibutuhkan sebagai justifikasi kualitas sebuah karya? Ketika
Barbra merasa ia tak pernah melahirkan karya besar, sebetulnya apa sih definisi
‘besar’ itu? Masuk daftar buku terlaris setahun penuh? Terkenang sepanjang
zaman?
Meskipun pernah mencapai semua itu, penulis
kreatif tetap saja bisa terserang depresi. Seperti yang disebutkan Jamison,
salah satu ciri penulis kreatif adalah keengganan untuk berpuas diri. Setelah
mendapatkan pujian untuk karyanya, lantas apa selanjutnya? Mereka kembali
gelisah, ingin meningkatkan kualitas dirinya, sekaligus mempertahankan pujian
yang disematkan kepada mereka. Kalau bisa mendapatkan lebih banyak lagi pujian.
Padahal, menulis setelah itu bukan menjadi lebih
ringan tapi justru lebih berat. Hal ini karena para penulis kerap terperangkap
oleh berbagai bentuk ‘pujian’, apakah itu pemuatan di media massa ternama,
komentar kritikus, daftar buku terlaris, atau pemberian penghargaan tertentu.
Tanpa disadari, penulis kerap membiarkan diri didefinisikan sebagai ‘pemenang’
atau ‘pecundang’ dengan standar-standar yang sebetulnya selalu berubah dan bisa
diperdebatkan. Penulis kadang lupa bahwa terlalu banyak menyandarkan ukuran
pada itu semua justru bisa mengantarkannya lebih cepat pada kematian dalam
berkarya, yang pada akhirnya malah bisa menyebabkan depresi.
Mati muda dalam karya bisa jadi keberuntungan
yang besar. Tapi jika bisa mati di usia 81 dengan deretan karya seperti
Pramoedya Ananta Toer, kenapa tidak? Ada yang bilang, Chairil mungkin tak akan
melegenda seperti sekarang jika tak mati muda. Ah, siapa yang tahu? Kalau saja
ia bebas depresi dan hidup sehat, jangan-jangan justru dia yang bisa jadi orang
Indonesia pertama yang meraih Nobel kalau hidup sampai lanjut usia.
Asal tak kemudian ia tetap berakhir sama dengan
Hemingway. ***
7048 Kali